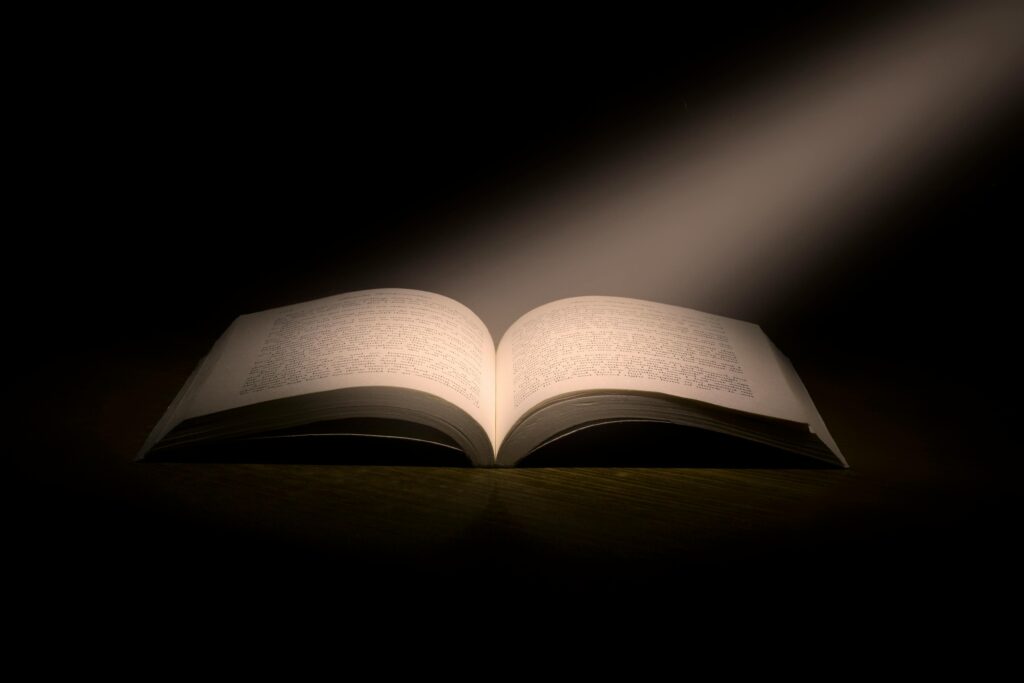Di suatu masa ribuan tahun silam, sebelum huruf-huruf dikenali oleh banyak orang, sebelum kata-kata bisa dicetak di halaman putih, manusia sudah berusaha mengabadikan pikiran dan perasaannya. Mereka mengukirnya di batu, mengguratkannya di daun lontar, menulisnya di atas papirus Mesir dan kulit binatang yang diproses menjadi lembaran halus. Tulisan-tulisan itu, meski terbatas, menjadi awal dari sebuah kisah besar: kisah penerbitan.
Peradaban seperti Mesopotamia dan Tiongkok kuno telah lama mengenal tulisan. Tapi hanya segelintir orang yang punya akses untuk membaca atau menuliskannya. Tulisan adalah milik para pendeta, raja, dan kaum terpelajar. Ilmu pengetahuan masih tersembunyi, hanya untuk mereka yang berkuasa. Buku adalah barang mewah.
Namun, pada abad ke-15, di sebuah bengkel kecil di Mainz, Jerman, seorang pria bernama Johannes Gutenberg menciptakan sesuatu yang akan mengubah dunia: mesin cetak dengan huruf bergerak. Penemuan ini, meski terlihat sederhana hari ini, adalah revolusi kala itu. Dengan alat ini, satu buku tak lagi butuh bertahun-tahun untuk ditulis ulang dengan tangan. Buku bisa dicetak ratusan, ribuan, bahkan jutaan eksemplar. Ide bisa menyebar seperti api.
Gutenberg mencetak Alkitab sebagai karya besar pertamanya. Dan dari sana, dimulailah era baru. Di Eropa, mesin cetak menyebar dengan cepat. Kota-kota seperti Venesia, Paris, dan London menjadi pusat penerbitan. Buku tak lagi hanya milik gereja atau istana, tapi mulai masuk ke tangan rakyat. Inilah bibit revolusi pemikiran. Abad Pencerahan pun lahir, diiringi oleh ledakan ilmu pengetahuan dan literasi.
Lalu, datanglah Revolusi Industri. Mesin cetak berevolusi menjadi lebih cepat dan kuat. Surat kabar mulai muncul. Buku bacaan menjadi lebih murah. Penerbit profesional bermunculan. Dan ketika abad ke-20 tiba, penerbitan bukan hanya industri, tapi juga kekuatan sosial-politik yang besar. Ia membentuk opini, menggiring perdebatan, dan menjadi alat perjuangan.
Namun kisah ini tidak hanya terjadi di Barat. Di ujung timur dunia, di kepulauan yang kelak bernama Indonesia, kisah penerbitan punya alur yang tak kalah dramatis.
Di masa lampau, nenek moyang kita juga menulis. Mereka menggunakan aksara-aksara tua di daun lontar, menuliskan kisah-kisah dewa, petuah hidup, hingga ramalan bintang. Tapi seperti di tempat lain, tulisan adalah milik kaum terbatas.
Segalanya berubah ketika Belanda datang. Di bawah kekuasaan VOC dan kemudian Hindia Belanda, penerbitan mulai hadir dalam bentuk baru—modern, tapi juga penuh kontrol. Salah satu tonggak penting adalah berdirinya Balai Pustaka pada 1917. Ironisnya, lembaga ini dibuat untuk “mengawasi” bacaan pribumi, tapi justru menjadi tempat lahirnya sastra Indonesia modern. Lewat lembaga ini, dunia mengenal Sitti Nurbaya, Salah Asuhan, dan para penulis hebat lainnya.
Penerbitan kemudian menjadi senjata perjuangan. Di awal abad ke-20, surat kabar seperti Medan Prijaji menjadi suara rakyat yang menentang penjajahan. Di balik mesin cetak, para pejuang menuliskan semangat merdeka. Di balik lembaran buku, mereka menyelipkan mimpi tentang bangsa yang bebas.
Saat Indonesia merdeka pada 1945, dunia penerbitan pun ikut bangkit. Pemerintah mendorong penerbitan buku pelajaran, buku agama, dan karya sastra. Penerbit-penerbit swasta mulai tumbuh, membawa warna dan suara yang beragam.
Namun, masa Orde Baru membawa angin yang berbeda. Penerbitan tumbuh, tapi dibayangi sensor dan pengawasan. Banyak buku dilarang. Banyak suara dibungkam. Tapi seperti biasa, dunia penerbitan selalu menemukan celah untuk bertahan. Di lorong-lorong toko buku kecil dan lewat buku-buku bajakan, ide terus menyebar.
Lalu datanglah era digital. Internet mengubah segalanya. Buku bisa dibaca di layar, diterbitkan sendiri oleh penulis, dan dijual hanya dengan klik. Toko buku bergeser ke toko daring. Media sosial menjadi ruang baru untuk promosi dan diskusi. Namun, tantangan juga muncul: pembajakan, informasi palsu, dan menurunnya minat baca.
Kini, penerbitan tak lagi hanya soal kertas dan tinta. Ia adalah suara. Ia adalah perlawanan. Ia adalah jembatan dari pikiran ke pikiran, dari generasi ke generasi.
Dan meski bentuknya terus berubah—dari papirus ke pixel—esensinya tetap sama: menyampaikan cerita, menyebarkan pengetahuan, dan menjaga nyala pemikiran manusia.